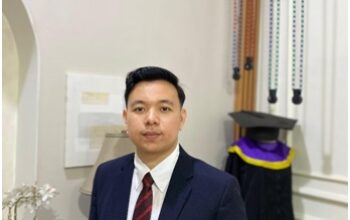Bencana Alam atau Akibat Kebijakan Manusia?
Akhir November 2025 memperlihatkan bagaimana kerusakan ekologis kembali menghasilkan penderitaan massal. Banjir bandang dan longsor melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, hingga Aceh, menewaskan ratusan jiwa dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi. Laporan internasional berjudul Landslides and flash floods on Indonesia’s Sumatra island leave at least 23 dead and dozens missing oleh jurnalis Binsar Bakkara untuk AP News menggambarkan bagaimana banjir bandang menyapu pemukiman, menghancurkan jembatan dan akses jalan, serta meninggalkan kerusakan parah pada infrastruktur (Bakkara, 2025). AP News kemudian memperbarui laporan korban melalui artikel Death toll from floods and landslides on Indonesia’s Sumatra island rises to 164 oleh Niniek Karmini dan Kasparman Piliang, menunjukkan eskalasi dampak yang mengerikan (Karmini dan Piliang, 2025).
Media nasional juga mencatat skala tragedi. Tempo dalam artikel Update BNPB: Korban Tewas Bencana Sumatera Jadi 442 Orang mengutip data BNPB bahwa korban meninggal mencapai 442 orang dan ratusan lainnya masih hilang. Sementara laporan Duka Mendalam dari Utara Sumatera: 442 Orang Tewas dari Minangkabaunews menggambarkan kehancuran sosial, ekonomi, dan emosional yang dialami warga.
Banyak analis dan aktivis lingkungan menilai deforestasi besar besaran untuk industri sawit, tambang, dan kehutanan komersial memperburuk banjir dan longsor. Di sejumlah titik, wilayah yang dilanda banjir berada dalam konsesi perkebunan atau penebangan kayu. Bencana yang seharusnya bisa diredam menjadi tragedi kemanusiaan karena kerusakan ekosistem menghilangkan daya tahan alami lingkungan.
Dengan demikian sangat jelas bahwa bencana ini bukan semata hujan ekstrem. Ia adalah akibat dari pemutusan relasi manusia dengan alam, dan relasi itu diputus oleh sistem ekonomi dan kebijakan, bukan oleh masyarakat adat.
Keterputusan Negara dari Kearifan Ekologis
Pemerintah selama ini berupaya menangani bencana dengan respons tanggap darurat, namun gagal mengatasi akar persoalan. Kebijakan lingkungan masih berpijak pada paradigma pertumbuhan ekonomi, di mana hutan dianggap aset negara untuk dieksploitasi demi investasi. Sistem ini menempatkan masyarakat adat sebagai hambatan pembangunan, bukan mitra konservasi.
Penelitian Purba (2020) menunjukkan bahwa 63 persen konflik tenurial di sektor kehutanan terjadi karena tumpang tindih antara konsesi industri dan wilayah adat. Ini membuktikan bahwa negara terus mengabaikan tata kelola ekologis berbasis nilai yang telah terbukti berhasil menjaga keseimbangan alam.